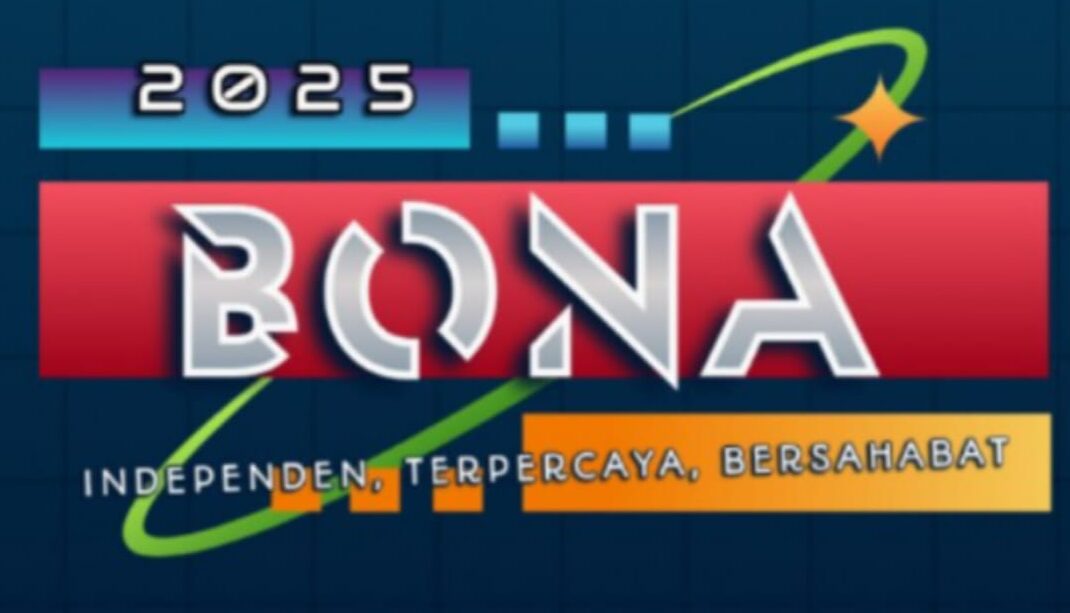BONA NEWS. Aceh. – Sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di tanah Sumatra bagian utara, tepatnya di Kuala Batu, wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Di pagi yang tampak biasa itu, ratusan prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat mendarat dengan satu misi: menyerang dan membinasakan. Namun yang membuat serangan ini lebih mencengangkan, mereka datang bukan sebagai pasukan, melainkan sebagai pedagang—penyamaran yang berujung maut.
Peristiwa ini dikenal oleh sejarawan Barat sebagai The First Sumatran Expedition. Namun bagi rakyat Aceh, ini adalah hari berdarah, saat orang asing datang dengan muslihat, membunuh ratusan warga sipil, dan menghancurkan tiga benteng pertahanan kota pelabuhan.
Kronologi: Perdagangan yang Berubah Jadi Perang
Peristiwa bermula setahun sebelumnya, tepatnya tahun 1831, ketika kapal dagang AS bernama Friendship disergap sekelompok perompak di perairan barat Sumatra. Awak kapal melaporkan bahwa mereka dirampok di dekat pelabuhan Kuala Batu, yang saat itu merupakan pusat perdagangan lada dan rempah penting dalam jaringan ekonomi global.
Washington segera merespons dengan mengirim kapal perang USS Potomac, sebuah frigat besar yang diawaki lebih dari 300 marinir dan pelaut, dipimpin Kapten John Downes. Namun mereka tidak datang secara terbuka.
USS Potomac memasuki Kuala Batu pada awal Februari 1832 dengan mengibarkan bendera Belanda di tiangnya. Dari kejauhan, kapal itu tampak seperti kapal dagang biasa. Penduduk lokal, yang terbiasa menerima saudagar asing, tidak mencurigai apapun.
Pada malam hari tanggal 5 Februari, pasukan AS diam-diam diturunkan ke darat dengan perahu kecil. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, mereka menyerbu benteng pertahanan dan membombardir pelabuhan menggunakan meriam dari kapal induk.
Jumlah Korban dan Skala Serangan
Serangan itu berlangsung cepat dan brutal. Dalam hitungan jam, tiga benteng utama Kuala Batu jatuh. Rumah-rumah penduduk ikut terbakar. Banyak warga sipil yang terbunuh saat mencoba melarikan diri atau melindungi keluarga mereka.
Menurut catatan resmi Angkatan Laut AS, sekitar 150 hingga 500 orang lokal tewas. Sebagian besar di antaranya adalah penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam pembajakan kapal Friendship. Di sisi lain, korban dari pihak AS hanya dua orang tewas dan beberapa luka ringan.
Ketimpangan kekuatan sangat jelas. Tentara AS dilengkapi senapan laras panjang, meriam kapal, taktik militer modern, dan logistik lengkap. Sementara pasukan pertahanan Kuala Batu hanya memiliki senjata sederhana: tombak, pedang, dan beberapa meriam tua yang peninggalan Eropa.
Motif Serangan: Balas Dendam atau Intimidasi Global?
Di balik retorika balas dendam, banyak sejarawan melihat ekspedisi ini sebagai bentuk unjuk kekuatan imperialistik. AS pada masa itu belum menjadi kekuatan global seperti saat ini, namun ambisinya untuk mengamankan jalur dagang internasional sudah terasa.
Amerika merasa perlu menunjukkan bahwa mereka bisa menghukum siapa pun yang mengganggu kepentingan dagangnya. Maka Kuala Batu, yang dituduh melindungi perompak, dijadikan tumbal.
Namun investigasi mendalam tidak pernah dilakukan. Tidak ada bukti jelas bahwa otoritas Kuala Batu terlibat langsung dalam perampokan kapal Friendship. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa para bajak laut yang menyerang kapal tersebut beroperasi secara independen, tanpa sepengetahuan penguasa lokal.
Penyamaran: Strategi Licik yang Efektif
Hal yang paling mengejutkan dari ekspedisi ini bukan hanya skala serangannya, tetapi cara yang digunakan: penyamaran. USS Potomac menyembunyikan niat militernya dengan menyamar sebagai kapal dagang, mengibarkan bendera Belanda.
Taktik ini jelas melanggar norma etika perang pada masa itu, meskipun belum ada konvensi internasional yang mengaturnya secara formal. Namun bagi masyarakat Kuala Batu, kedatangan kapal dengan wajah damai lalu berubah menjadi penyerang dalam semalam adalah pengkhianatan yang menyakitkan.
Dampak Langsung: Trauma, Kehancuran, dan Keheningan
Setelah serangan itu, pelabuhan Kuala Batu tidak pernah lagi kembali seperti semula. Aktivitas perdagangan menurun drastis. Banyak penduduk memilih pindah atau mengungsi ke daerah pedalaman. Ekonomi lokal lumpuh. Politik Kesultanan Aceh pun ikut terguncang.
AS tidak pernah meminta maaf atas serangan itu. Mereka bahkan menyebut ekspedisi ini sebagai “berhasil dengan cemerlang”, dan menjadikannya contoh dalam pelatihan angkatan laut selama bertahun-tahun.
Salah satu ironi besar adalah kenyataan bahwa tragedi sebesar ini nyaris tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Buku sejarah sekolah tidak mencantumkan peristiwa ini secara detail. Di arsip-arsip Barat, peristiwa ini diceritakan dengan sudut pandang heroisme militer Amerika, bukan dari perspektif korban.
Saat Sejarah Tak Menyebut Korban
Kuala Batu hanyalah satu dari sekian banyak kisah perlawanan lokal yang dipadamkan oleh kekuatan global dengan alasan perdagangan. Namun dampaknya masih terasa hingga kini: luka sejarah, penghapusan narasi lokal, dan hilangnya jejak penting dari peta memori bangsa.
Hari ini, hubungan Indonesia–Amerika Serikat berjalan hangat, penuh kerja sama ekonomi dan diplomatik. Namun kisah seperti Kuala Batu mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu indah, dan tidak semua hubungan lahir dari saling menghormati.
Mengingat tragedi ini bukan berarti membenci, melainkan memahami bahwa kekuatan harus dikendalikan oleh etika, dan bahwa damai tidak bisa dibangun di atas kebohongan dan penindasan.
“Mereka datang sebagai pedagang, tapi tangan mereka memegang senjata. Kita menerima mereka dengan keramahan, mereka membalasnya dengan darah.” — (Kesaksian lisan warga Aceh, dikumpulkan dalam tradisi lokal, sumber tak tertulis)