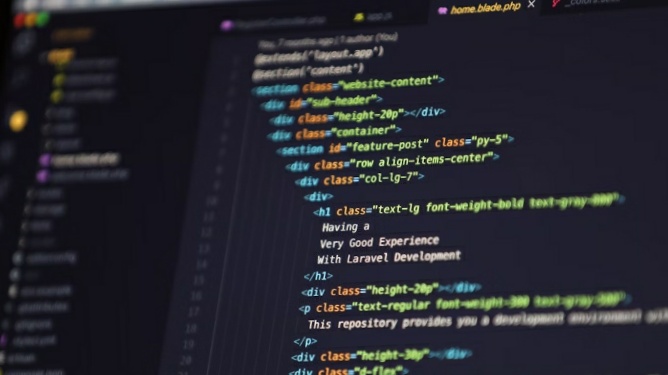BONA NEWS. Medan, Sumatera Utara. — Setiap hari, miliaran orang di seluruh dunia membuka ponsel, menggulir feed media sosial, dan membaca berita, meme, hingga komentar dari teman. Namun, di balik layar, ada kekuatan tak terlihat yang menentukan apa yang muncul di depan mata kita: algoritma.
Algoritma media sosial bukan sekadar barisan kode. Ia adalah sistem kecerdasan buatan yang mempelajari perilaku pengguna—apa yang kita sukai, tonton, dan komentari—lalu menyesuaikan isi layar agar kita terus bertahan lebih lama di platform tersebut.
Sebuah laporan dari Scientific American menyebutkan bahwa algoritma kini menjadi “penjaga gerbang informasi” yang menentukan apa yang kita lihat dan, secara halus, bagaimana kita berpikir tentang dunia di sekitar kita.
Bagaimana Algoritma Mengatur Feed Kita
Tidak banyak pengguna yang menyadari bahwa urutan postingan di media sosial tidak lagi kronologis. Sistem komputer menganalisis jutaan interaksi pengguna setiap detik: klik, waktu tonton, hingga jenis konten yang memancing emosi. Hasil analisis ini membentuk feed pribadi bagi setiap pengguna.
“Orang kini berinteraksi dalam lingkungan digital yang dikendalikan algoritma,” tulis Scientific American. Sementara itu, riset Pew Research Center menemukan bahwa hanya satu dari sepuluh pengguna yang merasa punya kendali atas konten yang muncul di beranda mereka.
Dengan kata lain, kendali atas informasi yang kita konsumsi kini sebagian besar berada di tangan perusahaan teknologi—bukan pengguna.
Algoritma dirancang untuk satu hal utama: meningkatkan keterlibatan (engagement). Semakin lama kita menggulir, semakin banyak data dan iklan yang dapat ditampilkan. Namun, efek sampingnya tidak sepele.
Konten yang memicu emosi kuat—marah, takut, atau sedih—lebih sering ditampilkan karena terbukti membuat orang lebih aktif berinteraksi. Fenomena ini dikenal dengan istilah amplifikasi emosional.
Akibatnya, informasi yang menyesatkan atau memecah belah bisa lebih cepat menyebar dibanding berita faktual.
Sebuah laporan The Guardian (2024) mengungkap bahwa algoritma TikTok dan YouTube dapat memperbanyak konten misoginis atau ekstrem hanya dalam hitungan hari, tergantung interaksi awal pengguna. Ini menunjukkan bagaimana sistem otomatis dapat memperkuat bias sosial tanpa intervensi manusia.
Gelembung Informasi yang Tak Terasa
Efek lain yang muncul adalah filter bubble—situasi di mana pengguna hanya disajikan informasi yang sejalan dengan pandangan atau preferensinya sendiri.
Hal ini membuat ruang digital terasa nyaman, tetapi sekaligus membatasi pandangan terhadap dunia yang sebenarnya jauh lebih beragam.
Dalam jangka panjang, echo chamber seperti ini dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Ketika masyarakat hanya mendengar pendapat yang seirama, ruang dialog publik menyempit dan perbedaan makin sulit dijembatani.
Transparansi yang Masih Gelap
Masalah lain adalah rendahnya transparansi. Platform seperti Meta, X (Twitter), atau TikTok jarang membeberkan detail bagaimana algoritma mereka bekerja.
Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) bahkan menyatakan bahwa pengguna “nyaris tidak memiliki kendali” atas bagaimana data pribadi mereka digunakan untuk melatih algoritma dan menyesuaikan konten.
Sementara itu, sejumlah pemerintah mulai meninjau regulasi baru. Negara bagian New York, misalnya, sedang mempertimbangkan aturan yang membatasi rekomendasi algoritmik bagi anak di bawah umur untuk melindungi kesehatan mental mereka.
Siapa yang Sebenarnya Mengendalikan?
Pertanyaan ini tidak punya jawaban tunggal. Di satu sisi, perusahaan teknologi jelas memiliki kuasa terbesar: mereka merancang sistem, menentukan metrik, dan memanfaatkan data.
Namun di sisi lain, pengguna juga memiliki ruang untuk mengendalikan—meski kecil—melalui kesadaran dan literasi digital.
Kita bisa mulai dari hal sederhana: mengikuti akun dari beragam pandangan, memverifikasi berita sebelum membagikan, dan mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak dikendalikan oleh algoritma yang hanya mengejar atensi.
Algoritma tidak sepenuhnya jahat, tetapi juga bukan sekadar alat netral. Ia adalah refleksi dari prioritas platform: menjaga pengguna tetap aktif selama mungkin.
Karena itu, memahami cara kerja algoritma bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang hak kita sebagai warga digital.
Pada akhirnya, kontrol informasi bukan lagi semata berada di server raksasa perusahaan teknologi, melainkan juga di kesadaran kita sebagai pengguna — apakah kita memilih untuk menjadi konsumen pasif, atau pembaca kritis di tengah banjir informasi tanpa batas.