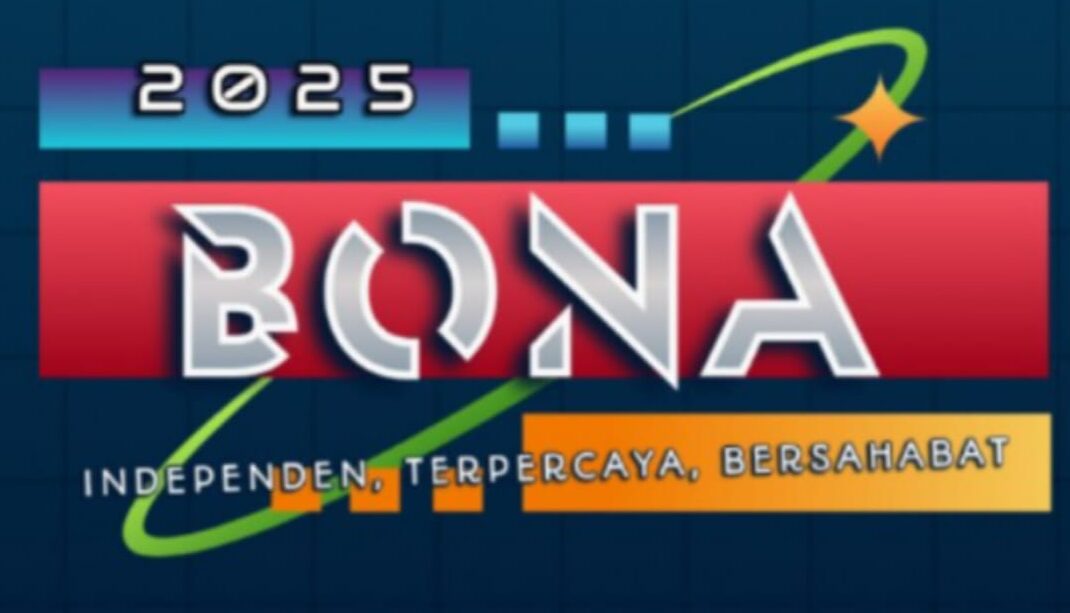BONA NEWS. Medan, Sumatera Utara. — Fenomena academic burnout atau kelelahan akademik kini menjadi isu serius di dunia pendidikan Indonesia. Tekanan belajar yang tinggi, sistem evaluasi yang menekankan nilai, serta ekspektasi sosial dari keluarga dan lingkungan membuat banyak pelajar kehilangan motivasi dan semangat belajar.
Riset dari Pusat Riset Psikologi Pendidikan (2024) menemukan bahwa lebih dari 60 persen siswa SMA di kota besar di Indonesia mengalami gejala kelelahan belajar. Data serupa juga muncul dari berbagai penelitian akademik di sejumlah universitas di Indonesia, yang menunjukkan pola serupa — pelajar semakin rentan mengalami kelelahan mental akibat tekanan akademik yang berlebihan.
Penelitian berjudul “Academic Burnout pada Peserta Didik Terdampak Pandemi COVID-19” oleh tim peneliti Universitas Sebelas Maret, Surakarta, menunjukkan bahwa sekitar 50 persen pelajar mengalami burnout tingkat sedang, dan 10 persen berada pada tingkat tinggi. Menurut penelitian tersebut, faktor penyebab terbesar datang dari beban tugas sekolah, tekanan nilai, dan kurangnya waktu istirahat akibat kegiatan tambahan seperti les atau bimbingan belajar.
Secara ilmiah, academic burnout didefinisikan sebagai kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental akibat tuntutan belajar yang berlebihan dan berkepanjangan.
Menurut Dr. Dwi Lestari, psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, burnout pada siswa biasanya muncul dalam tiga bentuk utama: kelelahan (exhaustion), sinisme terhadap sekolah (cynicism), dan perasaan tidak mampu (inefficacy).
“Pelajar yang mengalami burnout akan tampak lesu, kehilangan minat belajar, dan sering kali menurunkan performa akademiknya tanpa sebab medis,” jelas Dr. Dwi dalam webinar Kesehatan Mental Siswa Sekolah Menengah (Agustus 2025).
Riset di Universitas Pendidikan Indonesia terhadap mahasiswa Bimbingan dan Konseling menunjukkan bahwa 73,3 persen mahasiswa berada dalam kategori burnout tingkat sedang, dengan gejala paling menonjol berupa exhaustion dan cynicism.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pelajar tingkat menengah atau perguruan tinggi, tetapi juga ditemukan pada siswa sekolah dasar. Sebuah penelitian di SDN 57 Singkawang terhadap 41 siswa kelas IV–VI menunjukkan adanya korelasi antara burnout akademik dengan penurunan prestasi belajar.
Budaya Nilai dan Tekanan Sosial
Budaya pendidikan Indonesia yang sangat berorientasi pada hasil nilai menjadi faktor dominan dalam meningkatnya burnout di kalangan pelajar. Sistem pendidikan masih menempatkan keberhasilan akademik sebagai ukuran utama prestasi siswa.
Laporan Kemendikbudristek (2024) menunjukkan bahwa 45 persen orang tua masih menilai keberhasilan anak berdasarkan capaian nilai rapor, bukan pada keseimbangan antara prestasi akademik dan kesejahteraan emosional.
Menurut Asosiasi Psikolog Pendidikan Indonesia (APPI), tekanan ini diperparah oleh pengaruh media sosial yang memunculkan perbandingan sosial di antara siswa. Banyak pelajar merasa tertinggal ketika melihat teman sebayanya yang tampak “selalu berprestasi” di media daring, padahal tidak semua menampilkan realita yang utuh.
“Budaya kompetisi tanpa empati membuat banyak anak kehilangan rasa percaya diri dan makna belajar,” ujar Ketua APPI, Dr. Riza Fitriani, dalam konferensi nasional pendidikan mental remaja 2025 di Jakarta.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berperan besar dalam menekan risiko burnout.
Penelitian di SMA Muhammadiyah 8 Palembang terhadap 150 siswa menemukan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional siswa, semakin rendah tingkat burnout-nya. Siswa yang mampu mengenali dan mengelola emosinya cenderung lebih tahan menghadapi tekanan akademik.
Peneliti Rahmawati & Hidayat (2023) menulis bahwa “kecerdasan emosional bukan sekadar kemampuan sosial, melainkan juga mekanisme pertahanan mental terhadap tekanan belajar dan ekspektasi lingkungan.”
Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter dan keterampilan sosial-emosional menjadi strategi penting dalam mencegah burnout di kalangan pelajar.
Masalah burnout juga berkaitan langsung dengan krisis kesehatan mental remaja secara umum. Data yang dipublikasikan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (2025) menyebutkan bahwa 34,9 persen remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, dan sekitar 5,5 persen tergolong berat.
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan data 2022 yang hanya berada di kisaran 29 persen. Peningkatan ini sejalan dengan makin padatnya beban akademik, terutama di wilayah perkotaan.
Pemerintah kini menilai isu kesehatan mental sebagai salah satu prioritas utama dalam pengembangan Gerakan Sekolah Sehat, sebuah program lintas kementerian yang menargetkan keseimbangan gizi, kebugaran, dan mental positif di lingkungan pendidikan.
“Kesehatan mental sama pentingnya dengan kecerdasan kognitif. Guru BK dan wali kelas harus menjadi garda depan dalam mendeteksi dini burnout di sekolah,” ujar Dr. Iwan Syahril, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam konferensi pers di Jakarta, September 2025.
Beberapa sekolah menengah di Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya telah mengimplementasikan pendekatan student well-being atau kesejahteraan siswa.
Program ini mencakup konseling rutin, jam istirahat yang lebih fleksibel, dan aktivitas reflektif mingguan seperti mindful learning serta stress management workshop.
SMPN 4 Bandung, misalnya, bekerja sama dengan fakultas psikologi setempat untuk melakukan screening stres siswa setiap semester. Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan dalam gejala burnout setelah siswa mendapat sesi pelatihan manajemen waktu dan strategi belajar efektif.
Selain itu, Kurikulum Merdeka juga memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan beban pembelajaran sesuai konteks daerah dan karakter peserta didik. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi tekanan akademik berlebihan yang selama ini menjadi sumber utama burnout.
Meski demikian, tidak semua sekolah memiliki sumber daya memadai untuk mengelola masalah ini. Sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sering kali masih berfokus pada ketersediaan fasilitas dasar, bukan dukungan psikologis.
Peneliti dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, dalam laporan tahun 2024 mencatat bahwa pelajar di daerah 3T justru menghadapi tekanan sosial berbeda — bukan karena persaingan nilai, tetapi karena keterbatasan fasilitas, akses teknologi, dan minimnya dukungan belajar di rumah.
Hal ini menunjukkan bahwa burnout akademik bukan hanya persoalan “beban belajar”, melainkan cerminan ketimpangan sistem pendidikan nasional.
Untuk menghadapi masalah ini, sejumlah pakar pendidikan menyarankan langkah strategis, di antaranya:
- Integrasi pendidikan kesehatan mental ke kurikulum sekolah.
Guru BK dan wali kelas perlu mendapat pelatihan rutin mengenai deteksi dini burnout. - Penerapan sistem penilaian yang lebih holistik.
Tidak hanya menilai hasil ujian, tetapi juga partisipasi, kreativitas, dan kerja sama siswa. - Peningkatan peran orang tua.
Orang tua perlu memahami bahwa dukungan emosional lebih penting daripada tekanan akademik semata. - Pemanfaatan teknologi untuk manajemen stres.
Aplikasi student well-being berbasis digital kini mulai dikembangkan oleh sejumlah startup edukasi di Indonesia untuk membantu siswa memantau keseimbangan belajar dan istirahat.
Menata Ulang Paradigma Pendidikan Nasional
Fenomena burnout akademik menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih perlu bertransformasi dari sekadar pencapaian nilai menuju pendidikan yang menumbuhkan keseimbangan mental, sosial, dan spiritual siswa.
Sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kebahagiaan belajar.
Pendidikan yang sehat adalah pendidikan yang membuat anak ingin datang ke sekolah — bukan terpaksa.
Seperti dikatakan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim dalam forum Transformasi Pendidikan untuk Kesejahteraan Siswa (2025):
“Anak-anak kita bukan sekadar pelajar yang harus berprestasi, mereka manusia yang perlu tumbuh dengan sehat, utuh, dan bahagia.”
Membangun generasi cerdas saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan generasi yang tangguh secara mental dan berdaya secara emosional, agar mampu menghadapi dunia yang terus berubah tanpa kehilangan semangat dan makna belajar.
Sumber Referensi:
- Jurnal Bimbingan dan Konseling, Universitas Sebelas Maret (2024)
- Jurnal Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (2024)
- Kemendikbudristek RI, Laporan Pendidikan Dasar dan Menengah (2024–2025)
- Asosiasi Psikolog Pendidikan Indonesia (APPI)
- Sumatra.Bisnis.com, 24 September 2025
- Vokasi.Kemdikbud.go.id, Gerakan Sekolah Sehat (2025)